Tabumania, perlawanan terhadap genosida Israel ke Palestina tentunya tidak bisa dilepaskan juga dengan perjuangan kawan-kawan queer Palestina. Apalagi Israel juga melakukan pinkwashing, sebuah strategi propaganda yang dilakukan pemerintah Israel yang memanfaatkan hak-hak LGBTIQA+ untuk menampilkan citra progresif atau positif. Mereka ingin tampil sebagai negara yang toleran dan modern, dengan menyembunyikan kebijakan pendudukan dan aphartheid Israel yang menindas warga Palestina, baik queer maupun non-queer.
Komunitas LGBTIQA+ mulai menyadari manipulasi di balik pinkwashing ini. Semakin banyak kesadaran bahwa pembebasan queer dan trans tidak dapat dipisahkan dari pembebasan Palestina. Aktivis dan kelompok anti-pinkwashing telah mendorong hak-hak Palestina menjadi perhatian utama di berbagai acara Pride di seluruh dunia. Lebih dari 100 kelompok LGBTIQA+ mendukung seruan dari komunitas queer Palestina untuk memboikot Eurovision 2019 di Tel Aviv yang apartheid. Selain itu puluhan pembuat film queer telah menarik atau menolak pemutaran film mereka di TLVFest, festival film LGBT yang disponsori Israel. (sumber: https://bdsmovement.net/pinkwashing)
Nah, Queer Cinema for Palestine (QCP) sejak 2021 memberikan ruang etis alternatif bagi para pembuat film yang menolak menunjukkan karya mereka di festival film Israel tersebut. Pada Juni 2025 QCP mengisiasi No Pride in Genocide dan mengundang kelompok akar rumput, solidaritas, dan seni di seluruh dunia untuk mengadakan pemutaran program film pendek. Film-film yang diputar telah dikurasi oleh QCP. (sumber: IG @peretas_id)
Pada 30 Juni 2025 lalu, Qbukatabu, Peretas, dan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah bekerja sama mengadakan pemutaran dan diskusi film ini. Kegiatan solidaritas ini sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan dan merawat kekuatan kolektif queer menolak segala bentuk pinkwashing, militerisme, kolonialisme dan genosida Israel terhadap Palestina.(sumber: IG @peretas_id)
Ada 8 film yang ditayangkan dalam skrining film tersebut. Film-film tersebut antara lain: Abgad Hawaz (2024) film analog pendek berdurasi 1 menit digambar tangan oleh Robin Riad. Dalam film tersebut menggambarkan pelafalan alfabet Arab. Lalu ada Out of Gaza (2025) oleh Seza Tiyara & Jannis Osterburg, film berdurasi 9 menit ini menarik karena tidak diperankan oleh manusia, tetapi animasi lego. Film ini menceritakan seorang perempuan Palestina yang ingin pergi dari Gaza bersama teman-temannya. Ia berharap menemukan kebebasan di Barat. Namun, apa yang ditemui tidak sesuai harapan.
Selanjutnya Blood like Water (2023) oleh Dima Hamdan, film berdurasi 14 menit ini berdasarkan kisah nyata, menceritakan seorang pria gay yang menghadapi dua pilihan yaitu bekerja sama dengan Israel atau dipermalukan dan direndahkan oleh sesamanya sendiri karena ancaman rekaman hubungan seksualnya dengan pasangannya akan disebarkan.
Film keempat yaitu A Tangled Web Drowning in Honey (2023), oleh Tara Hakim & Hannah Hull, film berdurasi 8 menit mengajak penonton untuk memahami cara kerja batin seseorang dalam merenungkan cara mentintai dan tidak mencintai diri kita sendiri. Film ini begitu puitis, dengan kata-katanya yang indah.
Kemudian Aliens in Beirut (2025) oleh Raghed Charabaty. Film berdurasi 16 menit ini mengkombinasikan documenter dan fiksi. Berpijak pada peristiwa bersejarah ledakan Pelabuhan Beirut 2020. Menceritakan seorang pria melakukan perjalanan dari Toronto ke Beirut kemudian jatuh cinta dengan pria asing.
Dilanjutkan Palcorecore (2023) oleh Dana Dawud berdurasi 8 menit, film ini kombinasi antara tari, rekaman arsip dan video yang beredar di internet. Menggambarkan protret kehidupan Palestina.
Lalu I never Promised You a Jasmine Garden (2023) oleh Teyama AlKamli. Film berdurasi 20 menit menceritakan seorang perempuan queer yang diam-diam menyukai sahabat perempuannya. Dalam film ini menggambarkan bagaimana ia harus menahan emosinya selama mendengar sahabatnya menceritakan teman dekat prianya melalui telepon.
Diakhiri film Don’t Take My Joy Away (2024) oleh Omar Gabriel. Film berdurasi 7 menit berlatar kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Menggambarkan dua sahabat ysng menikmati kehidupannya, kemudian terjadi penyerangan yang menganggu dunia mereka. Dalam film digambarkan mereka berlari mencari tempat bersembunyi dalam kegelapan. Namun, ada kalanya mereka juga tetap mencari cahaya.
Setiap penonton memiliki kesan masing-masing terhadap film-film yang ditayangkan. Termasuk para pemantik diskusi setelah film ditayangkan. Mereka adalah Olla, seorang aktivis transpuan dan pengurus Ponpes Al Fatah; Edith, seorang konselor dan co-founder Qbukatabu; dan Cahya, seorang kritikus film dan penulis. Diskusi dimoderatori Naomi.
Diantara film-film yang ditayangkan, diantaranya meninggalkan kesan mendalam di antara mereka. Cahya memilih dua film; pertama, Palcorecore. Menurutnya dalam upaya penghapusan sistemik terhadap eksistensi Palestina, Kumpulan arsip jadi sangat penting untuk terus ditampilkan dan digaungkan. “Arsip yang dikumpulkan dalam film tersebut berfokus pada resistensi anak muda dan perempuan Palestina.”katanya.
Film kedua yang berkesan selanjutnya yaitu Blood like Water. Film yang berhasil membuatnya menangis, karena situasi yang riil atas queer Palestina. “Di satu sisi mereka harus menghadapi penindasan Israel, banyak yang mengalami blackmail, diperas, penjara. Di sisi lain mereka juga harus menghadapi cishetero patriarki yang masih melekat dalam masyarakat itu sendiri.”tambahnya.
Sementara Olla memilih Abgad Hawaz sebagai film yang membuatnya berefleksi diri. Mengingatkannya pernah meninggalkan agama kemudian ia balik lagi belajar lagi yang sempat hilang. “Aku belajar lagi tentan keyakinanku dan aku merindukan itu, aku mulai dari awal.”katanya.
Film kedua yang dipilihnya yaitu Alien in Beirut. Film tersebut mengingatkannya pada perjalannya saat ada ketakutan tidak diterima keluarga tentang identitas seksualnya. Ia pernah merasakan ketakutan akan diusir, akan mengalami persekusi, tetapi ternyata ia salah, ia bersyukur diterima oleh keluarga. “Dan aku menghargai setiap proses teman-teman semua, yang mungkin sampai saat ini tidak ada keberanian mengungkapkan siapa dirinya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan. kita tidak bisa memaksakan itu. Setiap orang pasti akan berada di titik di mana mereka akan mengalami proses kesiapan dirinya, siap atau tidak. Kita tidak pernah tahu di balik itu semua ada hal-hal yang mungkin selama ini pendam sendiri atau dia rasakan sendiri dan dia tidak berani mengungkapkan itu semua.”ungkapnya.
Blood in Water juga berkesan bagi Olla. Membuatnya menangis juga karena di film tersebut walaupun di awal seperti keluarga itu tidak menerima si anak dengan identitas gendernya, kemudian diterima oleh keluarganya. “Itu sangat relate banget, banyak teman yang berada di proses itu juga. Ada keluarga yang menerima ada yang menolak mereka, itu benar-benar terjadi. Mereka luar biasa, berdiri di kaki mereka sendiri, dengan yakinnya menjalani kehidupan mereka, bagiku itu sungguh luar biasa.”jelasnya.
Sementara itu Edith memilih dua film yaitu A Tangled Web Drowning in Honey dan Don’t Take My Joy Away. Menurutnya dua film tersebut mengingatkan dirinya ketika berproses dari berpaling dari isu ini karena tubuhnya merasakan kesedihan dan kemarahan serta hal yang tidak menyenangkan. Kemudian secara tegas menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Melalui film tersebut membuatnya berefleksi ada banyak duka, kemarahan dan rasa tidak nyaman ketika menyaksikan genosida di media sosial. Selanjutnya latihan pelan-pelan duduk dengan rasa tidak nyaman itu. Itu proses yang harus dilalui, meskipun tidak mudah.
“Kita perlu mengenali rasa ini, kita melihat peristiwa yang sangat brutal dan terjadi dalam waktu lama di depan mata kita, itu tidak nyaman. Di sisi lain kita juga bisa balik ke kesenangan-kesenangan kecil di komunitas kita, dengan teman-teman terdekat kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Sesuatu yang beriringan antara duka dan marah yang tidak bisa kita tanggung sendiri. Dan itulah pentingnya ada ruang ini, ruang solidaritas bersama ini. Karena kita tidak bisa menanggung sendiri. Karena terlalu berat kalau kita tanggung sendiri. Perlu kita rasakan bersama-sama.”tegasnya.
Di akhir acara, perwakilan peserta skrining film dan diskusi memberikan pernyataan solidaritas bersama-sama terhadap Palestina. Masing-masing perwakilan membawa potongan huruf yang dirangkai menjadi “No Pride in Genoside”, kemudian bersama-sama meneriakkan “Dari Jogja hingga Palestina, Tak Bangga dalam Genosida” ditutup yel-yel “Free free Palestine” berulang-ulang sebagai harapan segera berakhirnya genosida di Palestina.
Pernyataan solidaritas tersebut direkam dan dikumpulkan kepada QCP global. QCP juga akan mengunggah video-video dokumentasi pernyataan solidaritas tersebut di instagramnya @queercinema4palestine.
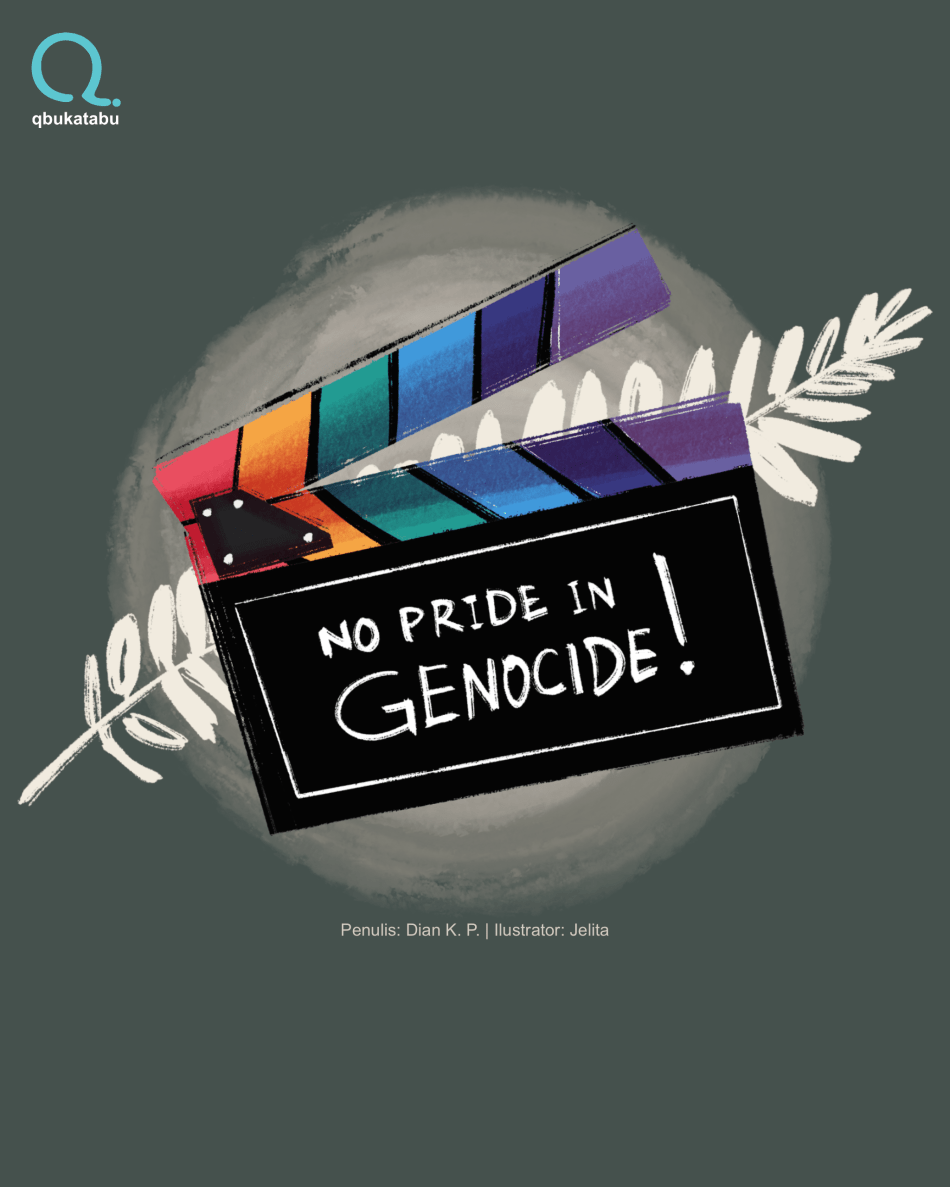
0 comments on “Queer Cinema for Palestina, Tak Bangga dalam Genosida”